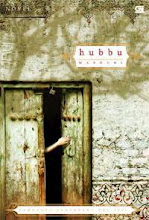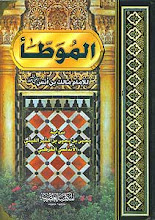Tak Ada W di Madura
: Ahmad Faishal
1
di balik tanah kapur, tanahmu
kutemukan terumbu, tetunas karang, muasal asal
juga garam yang asin dan terasa kekal
pun kutemukan kisah-kisah karang, puisi-puisi terjal
juga aksara yang berdebur laksana selaksa gelombang
melebur lebar---dileburkan angin, dilebarkan akal
kuingat desing peluru yang pernah kau tembakkan
dalam percakapan malam, ketika
kita sembah kegelapan
demi terang dan pencerahan
desing itu terus memburu
: “lebih baik berputih tulang
daripada berputih pandang”
peluru itu terus memburuku
aku pun berlari ke diri, berkaca, bahkan
menyeberangi kota-kota, selat-antara: selat Madura
membalik dusta di mata
menyulap bencana menjadi kencana
lalu mengerling pada desing pelurumu yang lain
desing yang menghias dedinding nafas
: “bila buruk muka, kenapa cermin yang dibelah…”
serasa berabad-abad, kita menahan nafas
meski serapah menggenang di darah
menggulung waktu
memanggil-manggil kenangan merah
untuk berdiwana di aorta, tapi…
kini kita termangu di kapal penyeberangan
mencoba menyeberangi dua luka yang saling berjauhan
antara maut dan kemaluan
antara nyali dan kehormatan
antara kawan dan lawan
di balik tanah kapur, tanahmu
kutemukan terumbu, tetunas karang, muasal asal
juga garam yang asin dan terasa kekal
sekekal perih ketika garam diparamkan ke luka
luka kita
yang disayat dengan pisau berkarat
dalam kesabaran abad
2
aku mengerti, Madura bukan tanah persegi
aku pun mengerti, kata kadang tak cukup untuk berbagi
di sini, ketika kau lafadkan abjad-abjad ke seberang kiblat
dan kutemukan pelafadan cacat…
---jawa kau eja jaba, kawin kau baca kabin
sawah kau teriakan sabah, warna dengan berna
bahkan nyawa kau geramkan dengan nyabe--
bahkan berpuluh-puluh kata yang menyimpan w berubah
ketika kau deraskan lewat lidah
lidahmu, melewati jeda
persimpangan suara yang menggugah dan menyisakan tanya
ketika aku tanya, kenapa kau lafadkan kata-kata itu dengan salah
kau pun berkata: “tak ada w di Madura’
mungkin kau tak sekedar ingin berbagi lewat kata
tapi juga lewat pandang mata, gerak,
juga setia pada jejak-jejak yang tertanam di sepanjang tanah
di sepanjang jalan, sejarah
mungkin kau telah mengerti, Madura bukan tanah persegi
sehingga tak rugi
meski telah begitu banyak memberi, hati
lewat berkah tanahmu, sungguh
tak aku temukan cacat di lafadmu,
karena b selalu melebur w
di jejak ranah pelafalanmu
sebagaimana nafas lautmu yang selalu mengubur
dendam dengan kematian
gelombang yang tak pernah berhenti mematri
karang sebagai pelabuhan…
3
di depan pusara
pusara yang diagungkan darah Madura
aku terbata
lelaki yang terbaring dari selatan ke utara
itu bangkit, di mata
kuburnya terbelah; terbukalah peta
kulihat titik-titik arah
kulihat begitu banyak noktah dan nama-nama
di silang silsilah
: namaku tertera di sana
Surabaya, 2007
Ada hantu di kolong ranjang,
yang setiap kali
Menyundut bokong, kau pun melantang
: ‘oh, laki-laki!’
Kau mungkin takut sebagaimana dongeng
Yang pernah dianyam oleh ibu-ibumu di lubukmu
: ceruk yang coreng-moreng
Bahwa hantu, bahwa laki-laki, punya seribu ranjau
Yang bisa membuatmu perih
Tapi kini kau tahu, hantu atau ‘laki’ bukan untuk ditakuti
Kau begitu mengimani: bahwa hantu, laki-laki, hanya punya batu
Tak lebih
Kini kau tahu, kau tak lagi Mariyem yang terpana
Oleng, tapi Mary yang mampu
Menenteng
Berpuluh lenguh..
Dan setiap kali, tamu membuka pintu
Mantramu pun bergemuruh, meluruhkan tubuh:
“Dari Semampir-Tanjung Perak,
ludruknya nobong
Silahkan mampir Om-om, Bapak-bapak,
kamarnya kosong...!”
Ah, tapi semuanya bukan hantu, hantu itu
Kini, sembunyi di bilikmu
Kau pun terus memandangnya, mengikuti ujung ekornya
Menemukan matanya,
Di gelap kamarmu
Sambil kau dekap boneka kelinci, bantal kumal
Juga bayangan gambar-gambar penyanyi, pedangdut
Yang menyepi di dinding, di setiap jengkal
Rumput
di dinding hatimu, kau pun melengking
“janganlah kau takut padaku, Hantu;
aku pelacur
yang saban malam begitu setia untuk mendengkur
memberi tempat pada nada-nada yang menjauh dari kubur
kubur kejantanan para tualang, lelaki kesepian...
bolehkah aku beri nama kau adam
: pacarku, yang pertama, yang telah direbut malam”
sehingga setiap kali hantu itu berdiam di kolong
ranjangmu, lalu menyundut bokongmu
kau pun kini berguman lirih: “o, laki-laki, laki-lakiku
yang sebapa-seibu...”
Kau pun mengaji sinyal lemah yang pernah jadi denah
Muasalmu melangkah:
mulai dari warung-warung remang, binaan babah
Petak-petak kamar bangunsari, bangunrejo, kremil
Bahkan dolly, atau bordil yang pernah menjadikanmu terpencil
Ke gerbong-gerbong sidotopo, di pinggir rel wonokromo
“di makam cino,
kembang kuning,
aku pun pernah membuat para sontoloyo
loyo, dan terkencing-kencing...”
pada ibu-ibumu yang kini tinggal abu
di ingatanmu, kau pun pernah berkata:
“semua yang datang, lalu mekangkang
lebih hina dari binatang ---mereka hanyalah pejantan
yang butuh tanda tangan....”
mungkin kau butuh seorang laki-laki
yang bisa menjadi hantu di benakmu,
di pikiran sederhanamu sebagai perempuan, juga ibu
seorang yang bisa menggambar
kesunyian geletarmu, dalam balsam asap rokok,
bir,
sampai ayam berkokok
dan terdengar bibir bertakbir
sungguh laki-laki itu,
hantu, yang saban malam
tenggelam di kamarmu, dan menyundut bokongmu
dengan lisong dan batu.....
merenggutmu ke malam
ke waktu lain, yang membuatmu bisa berpaling
dari denting pelir, kelir takdir yang telah memarkirmu
ke pinggir segala pinggir...
Sidoarjo, 2007
Siti, Ayo Kawin Lari
Di ruang kelas, aku baca cerita
yang sering membuatku berpusing kepala
cerita yang mengingatkanku pada pacarku
yang kepalanya juga sering terancam pecah
cerita yang berpangkal pada cinta tak berpunya
dan berakhir dengan duka carita...
“syamsul bahri berlari-lari ketika siti melamun di tepi
perigi, sambil memuji diri sendiri
: akulah perempuan abadi!”
Aku lalu mengambil penghapus dari ruang guru
Membaca sebentar, meski berlembar-lembar
lalu dengan ringkas kupangkas
Nama yang selalu membuatku was-was
: Siti
pada Syamsul Bahri, aku sisakan hidupnya
karena aku tahu Marah Rusli pun menyisakan hidupnya
dalam cerita,
meski siti telah mati..
aku begitu kawatir, kalau Marah marah lewat guruku
dan menggantungku
di depan kelas, sambil terus menerus menjejaliku
dengan kertas-kertas, yang panjang
dan tak bisa aku ringkas
aku pun menulis begitu tergesa di kertas
: “Syamsul Bahri hanya mati sekali;
sekali nafas
terpangkas, sesudah itu impas, lunas...”
Siti telah mati,
aih, ternyata Syamsul Bahri pun mati
tapi kisahnya terus bersambungan di tv
aku pun menulis surat pada pacarku, Siti terkasih
yang kini sedang menunggu di kampung
: “mari kawin lari, Siti,
mumpung kisah belum ditulis bersambung
di televisi!”
Sidoarjo, 2007
: Saudara Tua
mampirlah ke rumahku di pesisir, di pinggir pantai, di pinggir segala pinggir, tempat pasir memarkir takdir sebagai pembunuh; pasir yang saban hari tak lelah menjadi injakan kaki dan menjadi muara segala tubuh melabuh: tubuh lautan yang tak pernah mengeluh tapi menyulap keluh dengan nyanyian-nyanyian panjang
debur gelombang
kau akan mendengar karang ditabuh ombak, tubuh ditabuh riuh kehendak, kau akan melihat jejak-jejak retak yang membuatku tetap tegak meski gelap menggelegak bagai anggur memabukkan dan menyentak labirin kerongkonganku, kau akan menyaksikan…
ada gerak nan liar yang terpendam dalam diam
mampirlah ke rumahku; kau akan mengerti apa makna dari tepi: sepi yang berapi, merapi, sepi yang membahasakan diri di pucuk buih; bahasa-bahasa ombak yang menuntun mata; katupkan ufuk dengan cakrawala; rapatkan hiruk dengan rahasia
biduk asa yang tak berhenti untuk kembali
kau akan rasakan zenit meyentuh langit; doa-doa yang berdesing mengakrabi hening; doa putih, doa hitam; kau juga akan mendengar hingar doa yang memberi arus pada pasir, memberi ruh pada pasir, agar tubuh tak lagi berlabuh dalam gerak, tapi rubuh dan retak
lengan-lengan panjang yang merenda sejuta harapan
mampirlah ke rumahku, kau akan tahu, begitu banyak kanak belajar membunuh; mereka menghambur-hamburkan pasir di udara, dengan hembusan nafas yang telah terampas mata; mereka membuat patung-patung pasir gaib sebagai malaikat pencabut nyawa yang menyelinap di balik tangkapan indera
begitu dupa dibakar, doa dihentakkan dan bibir melaju: fuh! pasir-pasir akan beterbangan memintal korban, memburu setiap lubang yang terhampar di sepanjang kulit, bangkitlah kesakitan; pasir pun akan merasuki dan menyerbu darah dengan kekuatan-kekuatan langit; langit hitam ---sampai terdengar suara-suara ratap, pantai pun senyap, matahari gelap, awan berhenti, angin menepi; semuanya menyingkir untuk memberi jalan bagi kematian mengukir akhir
akhir penyaksian
kau akan tahu, bagaimana pasir-pasir itu menyatu darah, mengalir lewat aorta; arus hidup akan membawa bulir-bulir pasir lurus ke jantung yang berdegup, asal-akhir takdir Sang Hidup; pasir itu akan terus berasus ke ruas nafas, hingga hidup pun redup; jantung pun akan memberi jalan pada Sang Maut untuk bertitah: “berhentilah langkah, berhentilah darah!”
mampirlah ke rumahku di pesisir, kau akan mengerti, begitu banyak kanak bermain-main takdir, mainkan sihir-sihir pasir, rapalkan mantra-mantra pengusir; mereka berlarian di pantai-pantai tak beratap; membangun bukit-bukit dan patung pasir dari jasad yang telah lumat; jasad yang telah disepuh dengan doa-doa merah; doa kaum teraniaya, blap!
gelap!
Surabaya, 2007
istriku mengandung laut,
laut yang mencederai otakku dengan karang,
karang yang mengutip cakrawala
cakrawala dan kapal-kapal yang berlalu lalang
bahkan tenggelam dan terbakar di selat
selat yang selalu membuat istriku kumat
: “beri aku 1000 rakaat!”
aku pun ingat rabiah ---budak yang menapak
lewat batu, ke tangga penuh jejak wahyu
lalu sering kumat dengan mengganyang ribuan
rakaat dalam sekali malam dan sekali sikat
tapi istriku? mungkin ia sedang ngidam
begadang, malam-malam, di atas sajadah coklat
sambil mulutnya komat-kamit, penuh magnit
menarik, menombak dengan tepat
pikiranku yang sedang panik, dalam tidur
agar dengkurku tak lagi menjadi partitur
mimpi
mimpi tentang orang-orang yang terkubur
: kakek, nenek, buyut, canggah, wareng, gantung siwur...
aku bermimpi, tapi istriku sungguh telah mengandung
laut dan kumat dengan komat-kamit ribuan rakaat
dengan doa-doa panjang nan keramat
membanting harga diriku, dari lelap dan bisu
tentang asal-asul, tentang laut, tanah, udara, angin, api
juga sepi
ah, sungguhkah istriku bunting karena angin
laut, yang membawa berjuta plankton
ke ruang kosong... sungguhkah istriku hamil
karena gigil malam yang membugilinya diam-diam
di pantai, ketika lantai tak tepat lagi menjadi ranjang
tempat berbagi
ah, sungguhkah....
istriku mengandung laut
laut yang sering membuatku tercerabut
dari waktu; aih!
Sidoarjo, 2007
1
aku ingin kau memberiku sembilan mawar, yang kau bungkus
dalam tiga kardus, ditali dengan tiga temali,
lalu kau letakkan berjajar
menghadap pintu
: untukku, untukmu dan untuk rindu
mari bersulang, o daging yang rawan harapan
selanjutnya, aku ingin kau suguhkan tujuh cawan anggur, yang
kau tuang
dari lima botol, lalu kau sorongkan ke bibirku
lalu kau menghitung satu, tiga, lima dan tujuh
aku pun mabuk tubuh, mabuk gemuruh
aku akan menujumu dalam satu altar,
satu meja
sebagaimana satu kehendak yang labuhkan hasrat ke tubuhmu:
aku akan menujumu dengan dua kursi yang disatukan tubuh
sebagaimana kakiku dua, tanganku, mata, telinga, lubang hidung,
telinga...
juga rambut, juga sejumput rambut,
bahkan kelaminku yang selalu ingin bersatu maut,
mautmu
2
aku ingin kau memberiku tujuh
: bumi, langit, surga, neraka, juga hari
dalam sebuah nampan sesaji
dalam sebuah mimpi
aku ingin kau tahu, aku juga menginginkan lima
pasaran-hari, juga ihwal soal sudut bintang
yang selalu kau mimpikan dalam tidurmu
seperti igauanku yang tak pernah
lelah untuk terus memanggil namamu, seirama
dengan lubang
sembilan, membungkus tubuhku dengan mawarmu
: aku ingin kita bersatu
3
aku ingin menghidupi angka-angka di tubuhku
dengan angka di tubuhmu
1+1= setubuh...
Sidoarjo, 2007