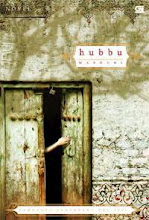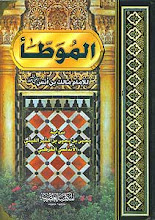Kejahatan Dulrokim
Aku memang mengenal sosok yang kau tanyakan. Aku biasa memanggilnya Dulrokim, seperti halnya warga lain memanggilnya. Jika kau bertanya, seberapa jauh kenalku dengan lelaki itu, aku tak bisa menjawab dengan pasti, karena nama panjangnya saja aku tak tahu. Aku hanya tahu nama panggilannya. Tetapi aku akan berkisah kepadamu sejauh kedekatanku dengannya selama ini, agar kau tahu gambaran Dulrokim dari sisi yang lain. Apalagi aku termasuk orang yang tak setuju dan sangat menentang tindakan orang-orang yang menghabisi nyawanya, lalu membakar jasadnya sampai menjadi arang. Pertama kali yang ingin kukatakan kepadamu, Dulrokim tidak sejahat yang dituduhkan. Malah ia kelewat santun untuk membunuh seekor nyamuk pun.
Kedekatanku dengannya dalam taraf biasa, tidak bisa dibilang istimewa. Dulrokim seorang yang sederhana, berasal dari sebuah kampung miskin yang terletak di sebelah barat kampung ini. Ia termasuk perjaka telat kawin. Baru setahun lalu, ia menikah dengan seorang gadis tetanggaku, ketika umurnya sudah menginjak 39 tahun. Rumahnya berjarak 7 rumah dari rumahku. Setiap kenduri, ia pasti hadir karena mertuanya sudah renta, dan ia sebagai wakilnya. Karena ia pendiam, banyak orang sungkan. Tetapi kalau sudah tertawa, banyak orang yang terheran-heran. Suaranya sangat keras dan gaya tertawanya terbahak-bahak.
Gara-gara tertawanya itulah aku berkenalan dengannya. Saat itu aku mengadakan kenduri untuk berkirim doa pada ahli kubur. Semasa hidup, almarhum ayahku pernah berpesan, ia minta selalu diselamati tiap tiga tahun sekali, agar arwahnya tenang di alam keabadian. Aku pun melangsungkan selamatan itu tahun lalu. Dulrokim aku undang sebagai tetangga baru. Seusai modin membacakan doa-doa, dilanjutkan dengan pembagian makanan ala kadarnya, aku pun berkisah soal ayahku, sampai pernik sekecil-kecilnya yang aku anggap menarik. Misalnya, ayahku yang suka kencing di dalam rumah tiap malam hari, karena tidak berani pergi ke pemandian dan sumur yang berjarak 5 meter di samping timur rumah.
Dulrokim langsung tertawa terbahak-bahak mendengar penuturanku. Aku memang agak tersinggung, tetapi karena aku belum kenal benar, aku hanya tersenyum. Begitu kenduri selesai, ia kudatangi lalu kusalami. Ketika kutatap wajahnya dengan seksama untuk pertama kali, tak ada kesan bahwa pribadi Dulrokim seburuk seperti yang sempat terlintas di benakku saat mendengar tertawanya, juga tak seperti yang dituduhkan orang-orang desa baru-baru ini, juga tak sebusuk seperti yang kau tanyakan tadi. Bahkan saat pertemuan terakhirku dengannya di telaga di depan masjid, dua hari lalu, ketika ia sedang mengambil air untuk persediaan minum keluarganya, wajahnya masih tetap sama. Tak terbersit kejahatan sedikit pun. Ia masih ramah, pendiam dan tak pernah mengobral kata, kecuali tertawanya itu.
Mungkin kau telah termakan omongan orang-orang, bahwa Dulrokim itu memiliki kekuatan guna-guna. Banyak desas-desus, ia bisa begini, bisa begitu. Omongan itu memang melebih-lebihkan. Aku bisa memastikan, ia nyaris tak bisa apa-apa untuk urusan yang berbau klenik. Ia hanya bisa mencangkul di sawah, mengambil air di telaga dan sembahyang rutin 5 waktu di masjid desa. Kemampuan membaca kitab suci Alquran pun hanya ala kadarnya. Untuk berbelanja keperluannya saja, ia tidak pernah melakukannya sendiri. Tidak tahukah kau, setiap kali Dulrokim merokok, ia lebih dulu harus memesan pada istrinya untuk membelikan tembakau di pasar desa? Begitu si istri datang, ia akan memasukan tembakau murahan ke dalam kantung plastik bersama klobot jagung yang sudah dirapikan. Ia lalu merokok dengan melinting sendiri. Lima hari sekali, ia pasti akan mengingatkan istrinya tentang tembakaunya itu.
Jika kau mendengar, ia suka keluar malam-malam, itu pun hanya ocehan orang saja yang dilebih-lebihkan. Hidupnya beralur segitiga: ke masjid, ke sawah dan di rumah. Ia tak pernah ke mana-mana. Ia pernah menginjak jalan beraspal pun mungkin hanya sekali seumur hidup, waktu ia kawin saja, karena untuk menikah ia harus ke kantor KUA (Kantor Urusan Agama) di kota kecamatan. Perlu kau tahu, ia keluar malam bukan untuk lelaku atau menyembah pohon beringin di tepi kuburan desa yang dianggap berhantu. Ia pergi ke dam kali di pinggir desa, hanya untuk berak. Ia selalu berak setiap malam ke sana, karena di rumahnya tak ada kakus. Ia tak mau nebeng di kakus tetangga sebab istri dan mertuanya sudah nebeng di sana. Ia tahu diri dan mengalah. Perihal kebiasaannya ini, aku sangat tahu, karena aku sering menemaninya ke kakus umum itu, sebab rumahku juga tak berkakus. Kau boleh percaya boleh tidak, tetapi itu memang kenyataannya, bila kau tanya kepadaku kebiasaannya yang sering keluar rumah pada malam hari.
Dan kemampuannya mengobati orang sakit gigi, itu pun berasal dari moyangnya. Aku bisa mengatakan, ia bisa mengobati sakit gigi juga secara kebetulan. Jika orang kampung berduyun-duyun kepadanya bila giginya sakit, itu karena sudah terlanjur percaya pada kemanjurannya. Mungkin kau ingin tahu soal kelebihannya tersebut, aku akan menunjukkannya kepadamu.
Pada awal musim penghujan tahun ini, gigiku sakit bukan kepalang. Gusinya bengkak. Memang banyak gigiku yang berlubang. Aku sampai mengeluarkan air mata saat menahan sakit yang tiada tara itu. Istriku langsung menyuruhku ke Dulrokim, karena kemahirannya sudah mashur di kampung. Setiba di rumahnya, aku diberinya rokok klobot, dan disuruh menghisapnya. Tetapi sebelumnya ia hisap lebih dulu rokok itu.
“Sebenarnya, ini hanya untuk keluarga, Kang!” katanya, kepadaku. “Pesan Eyang dulu begitu,”
“Tetapi banyak orang ke sini begitu?” sergahku sebisa mungkin, sambil menahan nyeri yang belum kunjung hilang.
“Aku tidak tega menolak mereka!” terang Dulrokim.
Oleh karena itu, soal tuduhan jahat yang dialamatkan kepadanya, juga aku ragu. Ia tak mungkin mampu menghilangkan nyawa manusia, bahkan hanya untuk menyakitinya. Kau mungkin harus mendengar kisahku soal kemurahan hati Dulrokim yang lain lagi, agar kau bisa menilai sendiri. Itu pun jika rasa percayamu kepadaku masih sekuat dulu dan tidak luntur.
Sebulan lalu, saat dia ingin mengganti pilar salah satu rumahnya dengan batang bambu baru, ia tak sengaja menebang bambu yang di atasnya terdapat sarang burung kutilang. Ia bukan seperti aku, atau kau atau orang-orang kampung lain, yang suka berburu burung atau mengambil sarang burung untuk mendapatkan anak-anaknya.
Ketika Dulrokim datang dari barongan1 dan memanggul sebatang bambu, kulihat ada noda merah di lengannya. Noda itu ternyata darah. Aku melihat darah itu mulai kering, tetapi lukanya masih tampak menganga.
“Kenapa tanganmu, terkena parang?” tanyaku.
Ia menggeleng.
“Lalu?”
“Aku terjatuh dan menimpa duri carang2 waktu mengembalikan sarang burung!” katanya.
Kau tahu apa responku mendengar dia berkata begitu? Aku langsung ingin tahu, karena bagiku sarang burung adalah dambaan. Jika sarang itu sudah berada di genggaman tangan, itu berarti karunia.
“Kamu kembalikan?” tanyaku, heran.
Ia mengangguk.
“Kenapa? Kalau kamu gak suka, buat aku kan bisa!” seruku.
“Ah, kasihan induknya. Nanti ia pasti mencari anak-anaknya!”
Aku lebih dari sekedar kaget mendengar jawabannya itu. Meski aku orang kampung dan hanya tamatan SMP, aku tahu, orang yang mampu berkata begini adalah orang baik. Jika kau dan orang-orang menuduhnya tidak baik dan keji, kukira itu salah sasaran. Kepada burung pun ia tak berani macam-macam, bagaimana ia bisa berbuat aniaya kepada manusia. Jelas ia tak punya keinginan untuk menyakiti, apalagi keinginan membunuh, meski dengan cara halus dan diam-diam.
Oke, aku tahu, mungkin kau ingin menjelaskan bahwa ada kasus lain yang melandasi dugaan dan tuduhan orang-orang kepadanya. Tetapi kasus itu sudah selesai. Dulrokim dengan berbesar hati sudah minta maaf, malah ia sangat menyesali keteledorannya. Ia juga bercerita kepadaku duduk perkara sebenarnya.
Petang itu, aku baru saja ikut jamaah Magrib, lalu duduk di serambi masjid. Tak biasanya Dulrokim datang dan menemaniku duduk-duduk di sana sambil menikmati pemandangan di telaga, karena biasanya ia akan langsung pulang begitu shalat usai. Kulihat wajahnya begitu murung. Selama ini aku tak pernah melihatnya wajahnya semendung itu. Aku tanggap, ia pasti sedang tertimpa masalah. Apalagi sore tadi aku sudah mendengar selentingannya. Ia pun berkisah tentang persoalannya pada waktu siang di sawah.
“Kang, aku tidak tahu, jika di kampung ini ada peraturan irigasinya. Aku tadi langsung membuka pintu air, tanpa permisi pada Kang Jali, yang sawahnya di atas garapanku. Kang Jali marah besar, aku dikatainya tidak tahu diri, tidak tahu adat dan sopan santun,” Dulrokim membuka ceritanya.
“Aku langsung membalik omongannya, karena aku merasa tidak bersalah. Untung ada Matroji, yang sawahnya berada di bawah sawahku. Ia lalu mengatakan peraturan irigasi kampung ini kepadaku. Jika tidak, mungkin aku tetap ngotot dan persoalannya menjadi lain, karena Kang Jali terus saja menghardikku sambil mengacungkan sabit,” lanjutnya.
“Terus?” pancingku.
“Ya, karena peraturannya demikian, berarti aku yang salah. Aku langsung minta maaf pada Kang Jali.”
“Beres kan?!” seruku.
Ia menggeleng. “Sepertinya Kang Jali masih marah. Ia pergi dengan mengumpat-umpat, misuh-misuh. Bagaimana lagi lha wong aku yang salah!” sambungnya.
Aku memang tak memberi jalan keluar waktu itu. Namun aku sadar, siapa yang tak kenal Kang Jali di kampung ini. Ia seorang yang tak ingin disepelekan, ia bermartabat. Maklum keponakannya adalah lurah, dan besannya H. Misnan adalah pengusaha penggilingan padi yang paling kaya di kampung. Aku hanya menasehatkan agar ia bersabar. Jika ada waktu, ia kusarankan agar sowan ke rumah Kang Jali. Tetapi saranku itu ternyata sudah terlambat.
“Dari sawah tadi, aku langsung ke rumahnya,” potong Dulrokim.
Aku terkesima. “Terus?”
“Hanya istrinya yang menemuiku. Katanya, Kang Jali sedang istirahat, tetapi aku sudah berpesan pada istri Kang Jali, agar maafku disampaikan kepada suaminya. Bagaimanapun aku yang keliru,” tutur Dulrokim.
Dia tidak jahat bukan? Meski aku tidak tahu persis latarbelakang keluarganya di desa sebelah, tetapi dari omongannya dan tingkah lakunya sehari-hari, aku tahu, ia bukan orang yang suka bikin masalah. Jika kau ingin mendesakku, agar aku bercerita tentang kebusukannya, kukira kau tidak akan menemukannya dan kau menemui orang yang salah. Aku memang tidak seakrab yang dikira orang, tidak sedalam seperti yang kau kira, karena ada hal-hal lain yang aku tak mengetahuinya, seperti latarbelakang keluarganya yang aku sebutkan tadi, juga bagaimana hubungannya dengan istrinya, hubungannya dengan mertuanya yang sudah renta dan pikun serta pernik kegiatan keseharian dia lainnya. Tetapi aku bisa menjamin dia tidak akan memiliki pikiran membalas dendam, seperti yang dituduhkan.
Jika setelah peristiwa itu, Kang Jali jatuh sakit, penyebabnya bisa seribu satu lebih. Tidak bisa dipastikan, sakitnya itu karena digunai-gunai Dulrokim. Ia tidak sekeji itu. Sudah berulang-ulang kukatakan, ia tidak memiliki pikiran membalas dendam. Bahkan, setelah pertemuanku dengannya di serambi mesjid perihal usahanya minta maaf pada Kang Jali, ia masih terus berupaya agar Kang Jali memaafkannya. Terlalu naif, bila ada orang menuduh sakit Kang Jali karena ulah Dulrokim. Dulrokim bukan tukang santet yang ahli guna-guna dan bisa membuat orang jatuh sakit atau mati, ia malah tak tahu soal mengerikan yang satu itu. Aku pernah memastikan sendiri tentang kemahirannya soal guna-guna ini.
“Kau pernah puasa, agar bisa mengobati orang sakit gigi?” tanyaku, waktu aku minta bantuan mengobati gigiku, ketika nyeri gigiku terasa sudah berkurang. Waktu itu rokok yang diberikannya kepadaku sudah aku hisap dan hampir habis.
“Porsi makanku banyak, Kang. Mana kuat aku puasa!”
“Tapi kok manjur?”
“Kata Eyang, waktu berdoa, aku harus yakin. Aku hanya diberi doa oleh beliau, tak disuruh puasa, karena aku juga bilang ke beliau, aku tak kuat puasa,” tutur Dulrokim.
“Selain mengobati sakit gigi?” tanyaku.
“Tidak ada, Kang. Aku tak bisa apa-apa. Tadi aku sudah bilang, ini pun untuk kalangan terbatas, hanya untuk keluarga,” terangnya.
Kau perlu tahu, Dulrokim berkata kepadaku secara langsung. Aku mendapatkannya dari sumber pertama. Jika ada orang bilang, ia mampu lebih dari sekedar mengobati sakit gigi, kukira itu hanya bualan. Kau juga perlu tahu, aku percaya padanya karena ia tak pernah berbohong dan menyakiti siapapun. Maka aku sendiri heran, bagaimana ia bisa dituduh dengan sangkaan sekeji itu: tukang santet. Kukira jika penanda dakwaan itu hanya mimpi, itu penanda yang salah kaprah. Kukira mimpi yang diwartakan Kang Jali adalah malapetaka. Bukankah tak ada yang tahu pasti kebenaran mimpi? Bisa saja Kang Jali mengarang cerita mimpinya itu, karena siapapun tak bisa menyanggahnya karena yang mengalami Kang Jali sendiri. Bisa pula Kang Jali memang bermimpi demikian, tetapi bagaimanapun mimpi tak bisa langsung dikaitkan dengan kenyataan dan dipastikan demikian adanya.
Terus terang aku sangat bersedih, ketika Kang Jali menceritakan mimpinya pada semua orang yang datang ke rumahnya saat membesuknya. Apalagi sebelumnya, kabar tersiar demikian gencar bahwa Kang Jali punya masalah dengan Dulrokim. Ia selalu mengulang-ulang cerita mimpinya terhadap siapa saja: pada saat ia merasa tubuhnya sakit, malamnya ia bermimpi Dulrokim menaruh rambut di cangkir kopinya dan ia tak sengaja langsung meminumnya. Aku yakin kau sudah pernah mendengar mimpi itu dengan berbagai tambahan bumbu penyedap dan lebih lengkap. Intinya Dulrokimlah yang membuat Kang Jali tak bisa bangun dari tempat tidur, karena separuh tubuhnya lumpuh.
Aku sangat menyesalkan mimpi itu ditelan mentah-mentah oleh orang-orang lalu disebarkan dari telinga ke telinga dengan berbagai tambahan. Pada akhirnya menjadi gunjingan di berbagai kesempatan. Sakdawa-dawane lurung, isih dawa gurung3 . Mungkin kau tahu arti pepatah Jawa itu. Jika sakit dan mimpi itu mengenaiku, mungkin tidak masalah karena aku hanya warga kampung biasa. Tetapi ini terjadi pada Kang Jali, sosok yang dihormati dan terpandang di kampung ini, serta memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang desa. Kau tahu sendiri betapa kuat pengaruh Kang Jali di sini dan kau sendiri tahu seberapa terpandang dia di mata khalayak. Pengaruhnya tidak hanya kepada kepala desa, tidak hanya kepada besannya yang kaya raya, tapi juga kepada warga yang rata-rata pendidikannya rendah dan cara berpikirnya sederhana.
Aku sangat terpukul, ketika kemarin malam, warga beramai-ramai mendatangi rumah Dulrokim dengan dipimpin aparat desa. Baru kali itu aku melihat warga demikian kalap. Tanpa basa-basi, mereka menyerbu rumah Dulrokim, lalu menyeretnya ke halaman dan menghajarnya dengan berbagai siksaan. Mereka terus menggebuki dan melukai Dulrokim dengan benda apa saja, meskipun dari mulut Dulrokim melolong minta ampun, meskipun tangis istri dan mertuanya meraung-raung. Tetapi siapa yang bisa menahan amarah massa? Orang-orang malah berteriak: “Bantai dukun santet, cincang dukun santet, sate dukun santet!” Puncaknya, mereka menghabisi nyawa Dulrokim dengan kesadisan tiada tara. Sekujur tubuhnya tak lagi berupa tubuh. Kedua kaki dan tangannya patah karena memang sengaja dipatahkan, wajahnya hancur penuh luka, isi perutnya tumpah-ruah, tulang-belulangnya remuk, dan... Maaf, aku tak bisa meneruskannya. Maaf.
Waktu itu aku sangat marah, sedih, geram, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku pun tak kuasa menyaksikan semuanya, juga saat sekujur jasad Dulrokim yang berlumur darah dan tak berbentuk manusia itu disiram bensin lalu dibakar. Aku pun tak bisa menyaksikan, ketika rumahnya yang berdinding dan berpilar bambu itu dirobohkan massa. Hatiku sakit. Perih. Hancur. Aku merasa ngilu memikirkan nasib keluarganya kelak, termasuk nasib istrinya, juga mertuanya yang renta. Ini bukan semata-mata karena selama ini Dulrokim yang menjadi tulang punggung mereka, tetapi mengenai nama baik mereka di mata warga yang sudah hancur.
Ah, sudahlah. Aku memang tak kuasa memaparkan semuanya karena paparan tragedi ini sebenarnya masih bisa kau endus bila kau melewati puing-puing kediaman Dulrokim, serta bekas-bekas darah yang masih tercecer di sana. Kisah lengkapnya masih bisa kau dapat, bila kau datang ke kerumunan warga yang akan langsung bertutur tanpa perlu ditanya, tentang kegagahannya dalam pembantaian penuh amarah yang mereka sebut dengan penyerbuan demi ketentraman. Tetapi jangan lagi berharap aku memaparkan keburukan-keburukan Dulrokim. Aku ingin kau tahu, aku tidak hanya sedih, aku merasa sangat berdosa karena membiarkan pembantaian itu berlangsung. Aku tak habis pikir, di zaman begini masih ada orang mati gara-gara mimpi yang tak diketahui dengan pasti ujung pangkalnya, gara-gara kemampuannya mengobati sakit gigi, juga gara-gara ada seorang tokoh yang merasa dilangkahi martabatnya walau orang yang melakukannya tak sengaja dan sudah menyembah si tokoh untuk sekedar minta maaf. Aku berharap kau melihat semuanya dengan jernih karena Dulrokim bukan senista seperti yang dituduhkan orang, tak sejahat seperti yang disangka Kang Jali.
Aku berujar demikian, karena aku yakin kau bisa memahami dan menimbang masalah ini dengan lebih adil. Harapanku padamu sangat besar agar peristiwa ini terkuak dengan sudut pandang yang seimbang, sebab kau satu-satunya warga kampung ini yang telah menempuh pendidikan hukum di perguruan tinggi. Aku yakin pikiran-pikiranmu lebih dewasa dan lebih berisi dari aku, juga lebih berbobot dari sebagian besar warga desa yang rata-rata masih buta huruf. Aku berani berkata begini karena aku yakin kau mampu mengatasinya, meskipun kau putera Kang Jali.
Kalikepiting-Siwalanpanji, 2007
3 Sepanjang-panjangnya lorong, masih panjang tenggorokan. Artinya: sepanjang-panjang lorong, masih panjang omongan atau gunjingan orang.