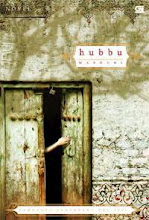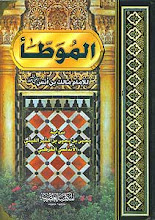Merindu Genre Puisi Epik di Jawa Timur
Oleh Mashuri
Puisi epik seringkali dipahami tidak bersemangat puisi modern oleh kalangan penyair dan sastrawan
Dari sisi kultur, puisi epik bisa mengungkai banyak hal yang tersembunyi dari lapis kesadaran masyarakat, yang tercerabut dari akar jati diri. Apalagi pengaruh luar sudah tak terbendung seperti sekarang ini. Pasalnya, epik selalu mengacu pada sejarah dan ingatan kolektif, yang dari sanalah bisa dirunut tentang berbagai hal di masa lalu dengan persimpangan dan pertemuannya. Dalam konteks ini, puisi epik bisa berupa tafsir kesejarahan yang kontekstual, sesuai dengan zeitgeist/semangat zaman, yang bisa sebagai tawaran/alternatif wacana dari arus hiperreal. Apalagi puisi epik juga bisa menimang banyak bidang, baik itu aras sastra, budaya, sosial, filsafat dan lain-lainnya. Sehingga kebutuhan pada pembacaan sosio-kultur yang holistis, yang pada dasawarsa saat ini sangat dibutuhkan, bisa tercukupi.
Jika dilihat dari segi sastra, bentuk puisi epik memiliki akarnya. Sejarah sastra
Potensi Puisi Epik
Dalam sejarah sastra Melayu lama, dikenal dengan cerita Panji. Cerita itu ternyata menyebar ke seantero Asia Tenggara, baik itu
Cerita Panji adalah salah satu contoh epik Jawa Timur, yang ditulis dalam bentuk puisi, meski berkembang pula dalam bentuk prosa di beberapa ranah seberang. Puisi epik yang lebih lama juga dapat kita jumpai dalam beberapa khasanah Jawa Kuno lain, yang tumbuh dan berkembang di Jawa Timur, seperti Pararaton (kisah tentang Ken Arok), Arjunawiwaha (tentang Prabu Airlangga) serta berbagai khasanah lainnya, yang transformasi pengetahuan dan literernya sangat sulit kepada generasi sekarang.
Dalam beberapa pagelaran sastra tradisional, sastra epik dalam bahasa Jawa, masih kerap dipentaskan. Biasanya dalam bentuk tembang, dan sering sebagai pegiring bentuk lakon atau drama. Hal itu karena dalam khasanah sastra tradisional, sastra umumnya ditulis dalam bentuk puisi, dengan beberapa aturan ketat, agar nanti bisa ditembangkan dan diiringi musik. Bisa dijumpai pada pagelaran wayang, ludruk, kentrung dan lain-lainnya.
Dengan adanya berbagai khasanah epik, yang tentu saja sekarang masih hidup dan dihidupi masyarakatnya, maka diperlukan sebuah penulisan kembali khasanah itu dalam bentuk puisi epik. Soal genre puisi epik ini bukan harga mati, tetapi ada beberapa pertimbangan yang perlu dicermati, yang menunjukkan kelebihan genre ini bila digarap bila dibandingkan dengan genre lainnya, semisal prosa. Kelebihan puisi epik adalah:
Pertama, pertimbangan peta perpuisian nasional, yang saat ini cenderung lirik, tanpa menawarkan hal-hal baru, dan terjebak pada homogenitas. Kedua, dinamika kesusastraan jatim. Pertimbangannya, selain puisi surealis dan gelap, tentu harus ada warna lain yang lebih menjanjikan dan memberi warna dan keragaman pada perpuisian Jawa Timur. Ketiga, dinamika kultur. Dengan adanya sentuhan dan tafsir baru pada kekayaan kultur lewat eposnya, maka dialektika budaya akan lebih dinamis karena puisi lebih bersifat psiko-sosial. Ketaksadaran kolektif bisa dirunut muasal dan akarnya. Terlebih lagi, puisi epik dimungkinkan bisa mendekatkan sastra dengan masyarakat, tanpa menurunkan kadar literernya. Selama ini, ada kecenderungan mendekatkan sastra dengan masyarakat/komunitasnya dengan cara menurunkan kadar literernya, yang tentu saja merupakan tindakan ceroboh dan bodoh.
Tentu saja, puisi epik dalam hal ini bukan terpaku pada ihwal normatif semata, tetapi juga merupakan hasil dari ‘eksperimentasi kreatif’ yang menjanjikan tawaran-tawaran baru. Bagaimanapun hakekat sastra adalah ketegangan antara konvensi dan inovasi (mengutip A Teeuw lagi). Dengan demikian, diharapkan muncul puisi epik dengan ruh pembaharuan, yang bisa saja bercorak antiepik, antihero dan lain-lainnya, atau bahkan memunculkan epik baru yang ternyata bisa lebih inspiratif dan imajinatif.
Sementara itu, jika ada penyair yang menulis puisi epik dalam dalam bahasa Jawa/Osing atau Madura, sebagaimana bahasa etnis subkultur Jawa Timur, tentu tidak menjadi soal dan lebih kental warna lokalnya. Namun karena ini menyangkut sumbangsih dalam peta perpuisian