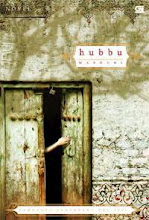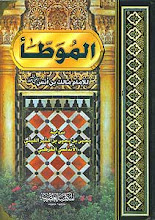Sajak Mashuri
Kidung Tanjung
Berjalan di utara, bukan hanya laut yang bergelora
Duri juga tumbuh bersama kaktus, mimpi pun
terbungkus nyeri ritus, nafas laut mendengus,
juga sekujurku yang diringkas panas, diringkus arus…
Cakrawala pun hangus,
ketika gelombang menerjang, angin berhumbalang
Bahkan rapal-mantram menjadi rangsum
ketika nelayan turun ---menjemput laut
dengan senyum dan kalut;
menawar maut dengan nyanyian peri dan liliput
Di sebuah tanjung, ketika ritus digenapkan dalam gaung
gelap dan agung,
laut kembali mewarta; kembali menguak duka lama:
kisah-kisah batu yang membujur ke debur ombak,
jejak yang bergerak dari retak
ingatan; tertuang dari zaman ke zaman
: Tanjung Kodok, selambang harapan keropok
Jiwaku pun dituntun alun gelombang ke purba hitam,
ketika katak-katak melata sepanjang peta pesisir,
ketika alir takdir masih nadlir, ketika cakap
cukup kerling mata, ketika kuda-kuda masih berderap
di jalan Deandles kelak dan terbata-bata
Sahdan saat janji ditimang dan dituang ludah api
Sang wali
: dendang Sunan Sendang nan resi
Segalanya mekar, atau terbakar di taman
terjanji: ketika angka-angka ditemali sepi azali
Kiblat pun ditarik kembali, dihadirkan di tepi pantai:
agar laut tak hilang gelombang, agar laut tak sujud
pada peri dan liliput
: “Aku akan merenda kubah, lewat sunyi dan madah
Kodok ngorek, kodok ngorek, ngorek pinggir kali,
teot teblung, teot teblung, teot teblung, hang-hung!”
Katak-katak bergerak ke pusar hutan
Jati di Mantingan
Mengetuk pintu perempuan datu: penjaga rindu
Kayu pun dilarung dari hulu
Dengan sekali sabda: katak-katak meraksasa,
berlompatan, meninggalkan lobang tapa,
memburu kayu yang menghilir…
Tapi berahi kelewat sunyi dilupa dalam riuh madah
: ‘kodok ngorek, kodok ngorek, ngorek pinggir kali
teot teblung, teot teblung, teot teot teblung…’
Ritus alam pun tertabuh lewat liuk tubuh
Indera tergiring ke sahwat purba
Mata bersua mata, daging mengingin daging
Berahi jelma pisau ---koyak dada dari patuh
Dua katak mabuk lenguh
Sejoli berenang di laut yang bergelora
segelora darah
keduanya berpinang dengan bahasa gelombang
kecup merayu, degup melagu
mengenal kembali lubang yang ditinggalkan
menutupnya kembali ---berkumpar pada pusar
farji-dzakar
Sabda pun menggelegar:
‘karena kalian telah terbakar ingkar,
kalian tak lebih dari tembikar’
Seperti lunglai tangkai padi yang ditegakkan kembali,
aku tatap hari lewat kecup matahari
Jiwaku pun kembali; mengingat sekat yang tercatat di
pantulan luka: di batu, yang membujur ke laut
aku pun bertanya, sungguhkah ia sibak ombak dengan sujud,
sungguhkah karang kapur yang tegak dalam umur
sebermula dari sabda; sabda yang dihantarkan bibir
bibir penafsir takdir
Aku daki batu itu, katak yang sendiri dan membeku itu
Ia tatap cakralawa laut Jawa dengan sungkawa, tapi
tak terdengar harap atau ratap, mungkin
sisa-sisa mimpi telah abadi dalam dongeng,
dalam kutuk cengeng: ia menunggu sang pekasih,
yang telah disapih; ia bergasing dalam penantian,
bercakap dengan kecipak ombak lewat lisan berkerak
di pupilku, fosil itu tak henti menggigil
karena sebagian dirinya gumpil,
terasing di seberang, nun jauh
sejauh aku menafsir bahasa terumbu
Berjalan di utara, bukan hanya laut yang bergelora
Surabaya, 2009
Sajak Mashuri
Sihir Pesisir
: Herry Lamongan
mampirlah ke rumahku di pesisir, tempat pasir sering mangkir dari takdir; pasir yang saban hari tak lelah merekam jejak-sementara dan menjadi muara segala tubuh berpeluh; tubuh melaut yang tak pernah mengeluh tapi menyepuh keluh dengan kasidah panjang: debur gelombang
kau akan mendengar karang ditanak ombak, tubuh ditabuh riak, kau akan melihat jejak-jejak geraham gemeretak; jejak yang membuatku tetap tegak meski arak menggelegak dan menyentak labirin kerongkonganku hingga serak, kau akan menyaksikan segalanya... meski ada gerak nan liar yang terpendam dalam diam, yang berpusar dalam samar...
mampirlah ke rumahku; kau akan mengerti arti dari tepi: sepi tapi berapi, sepi yang membahasakan buih ke perih tak terpahami; bahasa ombak yang menuntun mata ke palung tak berujung... ; sepi yang katupkan ufuk dengan cakrawala, rapatkan hiruk dengan rahasia; tepi biduk asa yang tak berbingkai
kau akan digamit zenit yang menyentuh langit; doa-doa yang berdesing mengakrabi hening; kau juga akan mendengar hingar doa yang meruap arus pasir, memberi ruh pada pesisir, agar tubuh tak lagi berlabuh untuk peluh, tapi jelma lengan-lengan panjang yang menderapkan sejuta harap
ah, tapi kerap doa-doa pun berkesumba, memasu sumur gelap
mampirlah... biar kau tahu, kini arus ‘lah berubah; banyak kanak belajar menghajar nyawa; mereka menghamburkan pasir di udara, dengan hembusan nafas yang telah terampas dari puja; mereka membuat patung pasir gaib sebagai kiblat malaikat pencabut nyawa berdiwana...
kau akan mendengar begitu dupa dibakar, doa-sesat dihentakkan: pasir-pasir akan beterbangan ke ruang samar, memintal korban, memburu setiap lubang tubuh dengan lenguh: ‘bangkitlah kesakitan!’ pasir pun merasuk dan menyerbu darah dengan kekuatan-kekuatan jelaga, sampai terdengar ratap, ratap panjang.... semuanya menyingkir, memberi jalan bagi kematian mengukir akhir siksa
pantai pun senyap, matahari gelap, awan berhenti, angin menepi
biar kau tahu ketika pasir-pasir itu menyatu darah, mengalir di aorta, lalu bebulir itu lurus ke jantung berdegup: asal-akhir takdir Sang Hidup; pasir itu terus berasus ke ruas nafas, hingga segalanya pun redup; jantung pun langsung memberi jalan pada Sang Maut bertitah: “berhentilah langkah, berhentilah darah!”
mampirlah ke pesisir, kini banyak kanak memainkan takdir, bermain sihir pasir, rapalkan mantra pengusir alir-Khidr; mereka berlarian di pantai-pantai seperti setapak tanpa akhir; membangun bukit dan patung pasir seamsal jasad yang ‘lah lumat; mulut mereka merajut puja-doa, meski sering pinta berkesumba, tapi kerap pula doa-doa merah
--doa kaum teraniaya...
Lamongan, 2009
Sajak Mashuri
Ironi Kota Singgah
: Hotel Itu Bernama Surabaya, Kawan
selat itu menyekat pipih geografi, kau menyebutnya: Surabaya
kota yang terbaca dari titik kecil: noktah hitam di peta,
di pinggir delta, di tepi laut Jawa
kau berhayat di antara kiblat-kiblatnya
ketika kita bertemu tanpa sekat, lalu kau
melihat sebarisan malaikat ---di Ampel, di Bungkul, berjamaat
atau tak terangkul di seberang semak-keramat
tapi aku terasing, buta, serupa pejalan yang tak sempat
melihat ujung tubuh: ber-Hujung Galuh, be-ruh
aku pun tak mampir berlabuh, tak parkir ke riuh
: bongkar-muat, ganti cawat, atau angkat sauh
kau tetap saja berkisah dengan angka, tahun-tahun
tapi aku seperti tersekat di seperempat abad pertama
pasca 1900: saat segala genap menjadi ganjil
dan segala luapan demikian gigil
saat gelora masih membenih di asa: meletup ke degup
indra, seperti pelari dengan api
yang tak redup, meski hati terseret ke jalan-jalan mati
jalan penuh mimpi!
lalu kau sebut 45: aku pun tersudut ke ruang nganga,
aku tak ingat sungguhkah gaung itu meraung
demikian agung; adakah tonggak: lingga yang menancap
tanah demikian tegap; lalu kau acungkan sahwat
: o, pahlawan, pahlawanku bertugu
tapi aku pun seasing budak belian kembali,
ketika segala temali mengikatku lagi
kutapaki jalan-jalan penuh hantu, perempatan berbatu
kulihat mercu suar membubung tinggi, berkabut
aku terpana ke pesona
: di lorong-lorong renjana
aku dipersilah dengan pantun penuh gairah:
“Tanjung Perak, kapale kobong!
Mangga pinarak, kamare kosong!”*
kau pun beringsut, seperti seorang yang mengigau
tapi aku bersorak, tanpa risau:
“inilah Surabaya, hotel tempat singgah
tapi bukan tempat berlibur, atau mengubur darah
segalanya lembur
seperti juga kapal-kapal yang berhenti lalu
berangkat, berganti-ganti
di sini, segala ranjang tak cukup dipandang
tapi dierami
silahkan merangkak, sebab segala sprei tak sengak
tak ada jerami, tak ada jejak
kecuali apak selangkang sendiri, yang kumal
ketika segala kemudi kembali ke asal
ke tujuan awal
di sini, kamar telah menjadi bujur sangkar
dan tak kenal lingkaran”
kau pun turun, menghitung kesunyian demi kesunyian
tapi biografi telah terbelah, garis-garis itu saling patah
kau dapati dirimu batu
tak berayah-beribu ---kau sangsikan jejak
-jejak panjang, segepok riwayat nan keropok
ihwal pertempuran di delta
antara ikan-buaya
lalu segalanya menjadi nama
kota, jalan, kampung, sungai, juga lorong-lorong keparat
tempat buaya darat bermunajat…
kau pun sangsikan segala sebab; kerna tak ada warta
yang lebih nyata kecuali kata-kata dusta
yang diulang ke berjuta
aku pun tersampir seperti gombal lusuh
di pinggir lenguh ---aku tak hirau pada riuh
sejarah ingatanmu
kudapati tubuhku, kurayakan tubuhku
seperti persinggahan di tengah perjalanan
yang tak mengenal kenang
kenanganku pun hilang bersama sunyi
: perempuan
yang selalu berharap diairi, di semak, di makam
di rumah-rumah yang berjajar dengan geletar
ketika kau mabuk
dan ambruk kedalaman luka tak berufuk
: silam!
kuangkat bir hitam, kuingat pada anak terkutuk
: diriku!
aku bangkit, kuangkat sauh, kulenguh langit
: “beri aku harapan untuk berlayar ke cakrawala
tanpa rasa luka oleh perih kenang dan ingat”
di seberang, kubangun kota-kota di hatiku
dengan batu-batu yang kucuri dari persinggahanku
agar aku tidak melupakanmu,
melupakan angka-angka
yang sempat kau hitung dengan deret aritmatika
yang tak kunjung kau ketahui jumlahnya
---kecuali waktu yang terus berputar
kau tetap tak tak ingin sesat di silam
dan terbenam bersama jangkar malam
: kini telah 180 derajat berputar
tak ada alasan untuk membangun sangkar
moga di milenium ini, kau tak lagi terpaku
pada paku silammu
tapi mengandangkannya di kalbu
lalu kau tulis deret rumus baru
: bahwa zaman telah berganti
hotel itu harus diperbarui, dicat dan pugar kembali
atau disucikan api…
Surabaya, 2006/9
* Di Tanjung Perak, kapal dilalap api
silahkan singgah sejenak, kamarnya tak berpenghuni